
Sejarah anak muda selalu lahir dari perlawanan. Kontradiksi sosial yang menginginkan kemerdekaan kedaulatan kultur. Suara anak muda mewakili kekecewaan terhadap kaum konvensionalis yang konservatif. Untuk mengelak dan bukan sekedar dianggap artifisial.
Bahasa lahir juga akibat perlawanan. Atas keterbatasan komunikasi dengan budaya setempat. Mewujudkan preskriptivisme linguistik karena kecenderungannya yang selalu kontekstual. Tapi itu tak bisa dicegah. Kontekstualitas bahasa bukanlah korupsi. Setidaknya secara konotatif. Itu pasti. Tergantung lidah dan isi otak. Bukan kadar intelektualitas.
Jakarta sebagai ibukota, tempat orang-orang Indonesia yang memang atau dianggap paling berkuasa, paling cantik, paling kaya dan sebagainya berada, penting dalam menyebarkan bahasa Indonesia.
Di Indonesia, bukan hal yang aneh kalau kita [contohnya] mendengar radio-radio di daerah (bukan Jakarta) yang segmennya anak muda, penyiar-penyiarnya berbicara dengan dialek yang seragam. Seolah-olah, kalau tidak memakai gaya Jakarta, itu bukan gaya anak muda. Gejala apakah ini? Hegemoni gaya bahasa tampaknya telah mengakar di setiap anak muda Indonesia. Akomodasi kerancuan bahasa yang dipropagandakan melalui representasi kekuatan budaya pop telah mengebiri makna-makna bahasa itu sendiri. Dampaknya mulai terlihat dari penggunaan-penggunaan literatur kontemporer yang seharusnya menjadi ajang kreativitas intelektual kaum muda. Bahasa Indonesia mengalami krisis identitas. Itu jelas. Baik reduksi makna maupun estetika. Kita terlalu malas untuk menggali keberagaman kata dari bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan asing lebih sering dipakai sebagai wujud intelektualitas dan kemalasan berpikir, daripada mencari padanannya yang seringkali dipertanyakan [atau diledek] entitasnya.
Akibatnya, Bahasa Indonesia cenderung mengalami pengkhianatan sistematik dari generasinya. Para penulis muda terlalu malas menelusuri rimba kata-kata. Sementara bahasa yang selama ini teraktualisasikan oleh keindahan sastra, berulangkali dipecundangi oleh arus utama yang katanya kontemporer. Hal ini menyebabkan dewasa ini banyak ditemukan para novelis, cerpenis, esais, namun belum berpotensi untuk menjadi sastrawan apalagi pujangga. Bahasa yang seharusnya dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu, hanya menjadi sekedar medium untuk menyampaikan hal-hal tersebut dengan proses-proses penyederhanaan yang [sangat] keterlaluan.
Kita harus mengakui, bahwa selama ini penggunaan bahasa lisan anak muda Indonesia hampir didominasi oleh bahasa anak Jakarta. Tak ada yang patut disalahkan. Karena selamanya anak muda akan mencari identifikasi sekaligus akomodasi gaya yang dianggap pantas dan mendapat pengakuan eksistensi dari komunitasnya. Kita hanya akan mampu menemukan jawabannya pada peranan media massa. Yang secara umum memang terpusat di Jakarta. Media [televisi, majalah, radio] memegang peran penting untuk membuat logat Jakarta menjadi logat yang seolah-olah paling keren dan enak didengar. Media massa dan industri menciptakan “kebutuhan” anak muda demi kepentingan pasar, yang dikampanyekan sebagai cara bagi anak-anak muda untuk keluar dari identitas yang diinginkan oleh orang tua. Dan menarik juga untuk mencermati bagaimana media massa telah menciptakan satu ikon anak muda tertentu pada tiap jaman. Lalu, harapan cuma mampu mengungkapkan bahwa segalanya adalah proses dan tak ada yang nisbi. Bahasa adalah sumber kekuatan dan identitas yang mampu menyatukan gerak kultur anak muda yang semakin dinamis dan berputar. Pada saatnya nanti, anak muda Indonesia [harus] mampu memahami bahwa kita adalah bangsa yang memiliki kekayaan bahasa dan diakui tingkat kerumitannya di mata dunia. [Dari berbagai sumber]
Bahasa lahir juga akibat perlawanan. Atas keterbatasan komunikasi dengan budaya setempat. Mewujudkan preskriptivisme linguistik karena kecenderungannya yang selalu kontekstual. Tapi itu tak bisa dicegah. Kontekstualitas bahasa bukanlah korupsi. Setidaknya secara konotatif. Itu pasti. Tergantung lidah dan isi otak. Bukan kadar intelektualitas.
Jakarta sebagai ibukota, tempat orang-orang Indonesia yang memang atau dianggap paling berkuasa, paling cantik, paling kaya dan sebagainya berada, penting dalam menyebarkan bahasa Indonesia.
Di Indonesia, bukan hal yang aneh kalau kita [contohnya] mendengar radio-radio di daerah (bukan Jakarta) yang segmennya anak muda, penyiar-penyiarnya berbicara dengan dialek yang seragam. Seolah-olah, kalau tidak memakai gaya Jakarta, itu bukan gaya anak muda. Gejala apakah ini? Hegemoni gaya bahasa tampaknya telah mengakar di setiap anak muda Indonesia. Akomodasi kerancuan bahasa yang dipropagandakan melalui representasi kekuatan budaya pop telah mengebiri makna-makna bahasa itu sendiri. Dampaknya mulai terlihat dari penggunaan-penggunaan literatur kontemporer yang seharusnya menjadi ajang kreativitas intelektual kaum muda. Bahasa Indonesia mengalami krisis identitas. Itu jelas. Baik reduksi makna maupun estetika. Kita terlalu malas untuk menggali keberagaman kata dari bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan asing lebih sering dipakai sebagai wujud intelektualitas dan kemalasan berpikir, daripada mencari padanannya yang seringkali dipertanyakan [atau diledek] entitasnya.
Akibatnya, Bahasa Indonesia cenderung mengalami pengkhianatan sistematik dari generasinya. Para penulis muda terlalu malas menelusuri rimba kata-kata. Sementara bahasa yang selama ini teraktualisasikan oleh keindahan sastra, berulangkali dipecundangi oleh arus utama yang katanya kontemporer. Hal ini menyebabkan dewasa ini banyak ditemukan para novelis, cerpenis, esais, namun belum berpotensi untuk menjadi sastrawan apalagi pujangga. Bahasa yang seharusnya dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu, hanya menjadi sekedar medium untuk menyampaikan hal-hal tersebut dengan proses-proses penyederhanaan yang [sangat] keterlaluan.
Kita harus mengakui, bahwa selama ini penggunaan bahasa lisan anak muda Indonesia hampir didominasi oleh bahasa anak Jakarta. Tak ada yang patut disalahkan. Karena selamanya anak muda akan mencari identifikasi sekaligus akomodasi gaya yang dianggap pantas dan mendapat pengakuan eksistensi dari komunitasnya. Kita hanya akan mampu menemukan jawabannya pada peranan media massa. Yang secara umum memang terpusat di Jakarta. Media [televisi, majalah, radio] memegang peran penting untuk membuat logat Jakarta menjadi logat yang seolah-olah paling keren dan enak didengar. Media massa dan industri menciptakan “kebutuhan” anak muda demi kepentingan pasar, yang dikampanyekan sebagai cara bagi anak-anak muda untuk keluar dari identitas yang diinginkan oleh orang tua. Dan menarik juga untuk mencermati bagaimana media massa telah menciptakan satu ikon anak muda tertentu pada tiap jaman. Lalu, harapan cuma mampu mengungkapkan bahwa segalanya adalah proses dan tak ada yang nisbi. Bahasa adalah sumber kekuatan dan identitas yang mampu menyatukan gerak kultur anak muda yang semakin dinamis dan berputar. Pada saatnya nanti, anak muda Indonesia [harus] mampu memahami bahwa kita adalah bangsa yang memiliki kekayaan bahasa dan diakui tingkat kerumitannya di mata dunia. [Dari berbagai sumber]


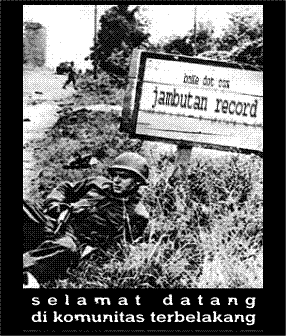
No comments:
Post a Comment