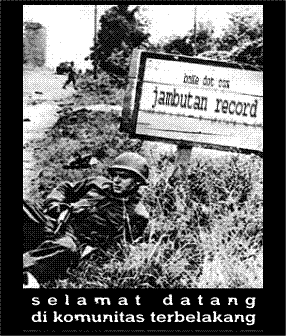Kami merindukan suara-suara berontak. Dari ujung-ujung gedung bertingkat dan sekarang berpagar mobil-mobil mewah.
Kami merindukan langkah-langkah berderap. Melaju bagai kuda binal di tengah padang menyala. Menggetarkan bumi pertiwi menjelang mati.
Kami merindukan wajah-wajah berpeluh pengorbanan. Tiada pamrih memperjuangkan sunyi.
Kami merindukanmu para pejuang. Yang sekarang sibuk berdesakkan meributkan eksisitensi.
Kami merindukanmu para seniman. Yang sekarang dinafikan oleh kemunafikan budaya.
Kami merindukanmu mahasiswa. Yang sekarang berkutat pada pragmatisme ilmiah. Dan terbuai oleh budaya-budaya instan.
Kami merindukan kedai-kedai kopi angkringan. Yang dulu menghasilkan ideolog-budayawan handal. Dan sekarang telah ditelan oleh warung-warung kapital.
Lalu kami harus bertiarap. Tergusur globalisasi jaman. Meratap di bawah atap-atap pembaringan.
“Teraniaya di tanah moyang sendiri. Hari suram. Mencekam.”*
“Bangsat. Bangsat. Hidup ini memang bangsat. Bila hukum tak pernah berpihak ke kita.”**
“Ketika rakyat lapar. Kalian berkelakar.”**
Sang pemimpin sibuk bercanda dengan sebatang boneka kayu. Para prajurit menahan tumit. Para menteri sibuk bersenggama dengan pelacur-pelacur politik. Para ulama mulai menggadaikan kitab-kitab suci.
Kampus-kampus mulai sepi. Masjid-masjid kembali sunyi. Rumah bordil semakin merintih.
Kami merindukan sesuatu yang entah. Untuk itu terlalu pasrah tertelan.
Masuk kampus siap jadi budak.
Masuk kantor jadi penjilat.
Masuk masjid [terpaksa] jadi imam.
Masuk pasar jadi korban.
Masuk terminal jadi preman.
Masuk rapat jadi aparat.
Masuk penjara jadi orang hebat.
Jadi penutur siap masuk kubur.
Lalu sekali lagi kami merindukan kalian yang entah.
Jogjakarta
* Dikutip dari lagu Teknoshit, Puisi dan Sampah
** Dikutip dari lagu Teknoshit, Realita